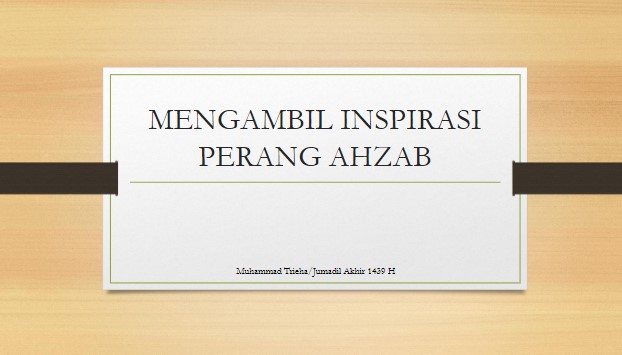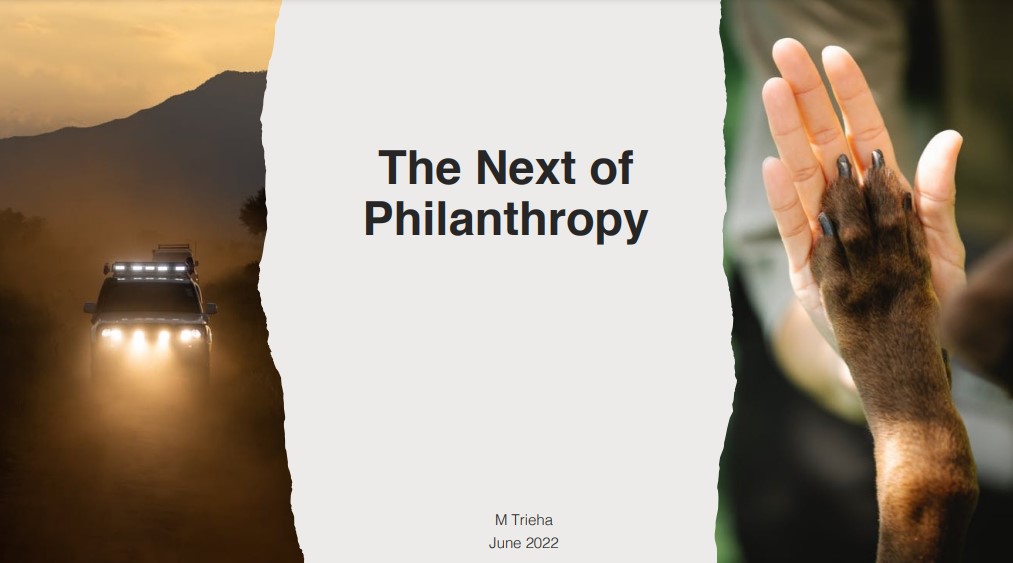Kemarin pagi kami diskusi tentang kepemimpinan. Muncul banyak perspektif baik dari latar pengalaman belajar di kelas, di buku maupun praktik di lapangan. Saya kok teringat ibu saya, buat saya dan mungkin kita semua, ibu adalah salah satu pemimpin dalam hidup kita melengkapi figur ayah sebagai kepala keluarga. Saya masih meyakini bahwa menjadi pemimpin tidak harus jadi kepala, karena kepala biasanya cuma 1 padahal terlalu banyak ruang kehidupan yang selalu membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan. Itu mungkin mengapa kemudian kita mengenal istilah pemimpin formal dan informal.
Lalu apa yang menarik soal pembelajaran kepemimpinan dari ibu saya? Ibu saya ber-statement bahwa rumah yang baik adalah yang banyak kursinya. Ini mengapa di rumah kami selalu tersedia banyak kursi di hampir setiap ruangan, sepertinya hanya kamar mandi yang gak ada kursinya. Mengapa? Ibu saya ingin setiap orang bisa mudah dan nyaman ngobrol bersama. Setiap ruangan rumah adalah tempat kita berbincang dan bercengkrama, bukan sekedar fungsional dalam definisi ruangannya. Ruang tamu bukan sekedar ruang menerima tamu, ruang tidur bukan sekedar untuk menidurkan badan, dan sebagainya. Ruang TV memang karena di sana ada TV-nya tapi dengan adanya kursi membuat ruangan tadi sebagai media kita menginteraksikan ide, gagasan dan rasa cinta kita sebagai anggota keluarga. Jadi setiap ruang memiliki nilai tambah fungsi yaitu sebagai ruang interaksi, dan kursi menjadi enabler-nya.
Tanpa sadar ibu saya sedang mendidik kami tentang bagaimana sebenarnya komunikasi langsung sangat penting dalam menciptakan keselarasan dan titik temu baik nanti dalam kepentingan politik, sosial, ekonomi dan sejenisnya hingga agama. Banyak salah paham terjadi karena kita malas untuk beranjangsana, bersilaturrahim dan tentunya berdialektika dari satu topik yang sederhana sampai yang perlu silat logika. Betul semua bisa tergantikan dengan sms, twit, BBM, tapi rasanya duduk santai di atas kursi saling berhadapan ditemani teh manis panas dan sepiring pisang goreng akan jauh berbeda rasanya. Di Jawa tradisi wedangan, minum teh/kopi berikut penganannya bebarengan, telah menjadi media ‘in search of wisdom’. Wedang/minuman; teh, kopi, jahe, STMJ hanyalah media untuk mensenyawakan jiwa walaupun secara pikiran tidak harus selalu pro atas suatu topik yang dibicarakan. Justru pro kontra itulah yang menghidupkan tradisi ‘wedangan’. Apakah ada hubungannya dengan kalimat bijak; “Urip iku sejatine mung mampir ngombe” (Hidup itu sebenarnya hanyalah seperti mampir minum)? Maaf saya bukan Ronggowarsito, yang pasti minuman telah melibatkan perannya begitu purba dalam sejarah manusia, dan kursi menjadi saksinya.
Ternyata kalau kita keliling nusantara kebiasaan yang sama banyak sekali kita jumpai. Mulai Aceh, Medan, Belitung, Lampung, Jawa, Sunda, Kalimantan, hingga ke wilayah timur Indonesia. Maraknya kedai kopi (yang kemudian diadaptasi menjadi Kafe) dari yang sangat tradisionil sampai modern menjadi terjemahan yang lugas bahwa sebenarnya kita membutuhkan media tatap muka untuk saling menginteraksikan hubungan kita. Tentu semua yang berlebihan itu tidak baik, ini juga berlaku untuk kebiasaan ‘ngopi’, kalau kelamaan dan malah jadi kebiasaan yang mendorong jadi tidak produktif tentu bukan termasuk dalam anjuran tulisan ini.
Jadi mengapa kita tidak memaksimalkan kursi-kursi kita untuk berdiskusi dan melingkarkan batin? Dari kursi tersebut kita bisa melempar ide kepemimpinan dalam aplikasi yang lebih jernih dan shahih serta menerima kebijaksanaan dalam cara lebih bijak, karena ini bukan rapat bukan indoktrinasi. Semoga dari kursi-kursi tersebut akan melahirkan pemimpin baru yang lebih amanah saat menduduki Kursi tanggung jawabnya.