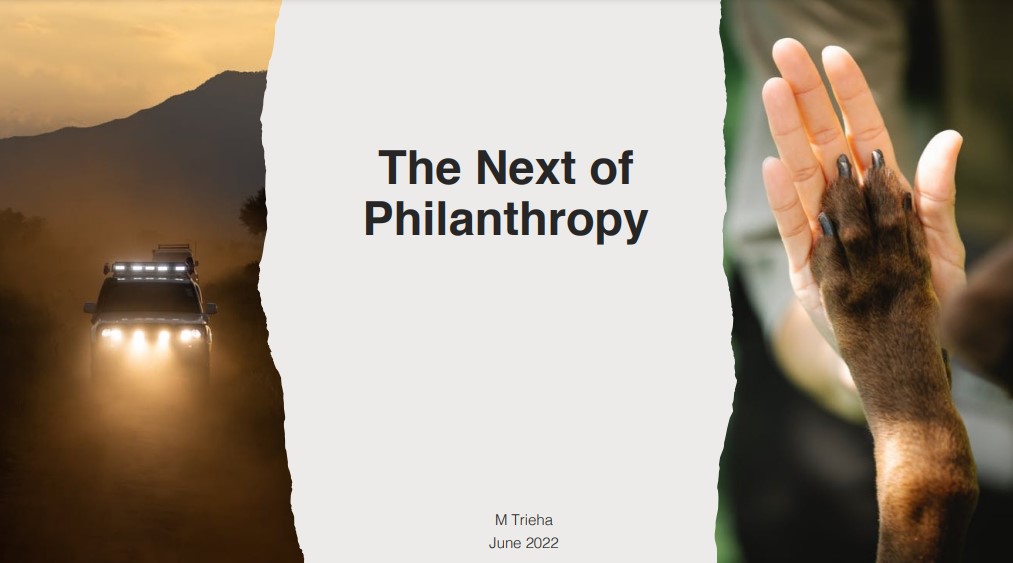Ingin kuingat masa dulu mahasiswa. Seperti biasa, mata ini tak cukup bisa menolak meniti baca deretan judul buku yang tergolek di gelaran lantai serambi sebuah masjid pagi itu. Bukan Di Negeri Dongeng, tanpa sadar buku itu telah terayun di tangan, dalam mimik tipis- guratan kata di cover belakangnya menarik simpati saya. Singkat cerita buku itu kini menyelinap dalam tas kecilku, untuk sebuah kredo yang selalu saya yakini bahwa BUKU ADALAH INVESTASI.
Belum lama terpindai seluruh ruas kata dalam setiap lembarnya, ingin betul saya menuliskan serupa. Tentang kisah nyata para pejuang yang banyak meneteskan keguruannya dalam ranah hati saya.
Izinkan penghormatan itu berangkat pada seorang guru yang sangat bersahaja, KH. Ahmad Dunuwi Hamim Allahu yarham. Dalam usia senjanya beliau selalu mengajarkan keramahan, bahkan begitu menghormati direktur kami yang jelas-jelas mantan muridnya. Baju putih dengan lipatan tajam bekas setrika mengingatkan saya tentang etika, tentang ilmu akhlaq dan hadits yang beliau ajarkan ke kami, siswa-siswa bengalnya. Malam itu berombongan kecil kami membesuk, dengan lirih saya bisikkan nama saya ke dekat telinganya, “Harmoko”, nama yang lebih akrab dipilihnya. Mata tua itu berkaca, senyumnya berat tanpa sanggup berkata. Kabar duka tiba sepekan setelahnya. Seluruh angkatan siang itu mengerumuni tanah makam, sebelum Ia menuju Tuhannya. Kekasihnya.
Tergetar pula saya pada retorika seorang tua. KH. Suprapto Ibnu Juraimi namanya. Malam itu dalam sebuah training, suaranya menggedor ruang spiritual saya. Tentang pentingnya berjuang, tentang urgensinya berdakwah. Jangan tanya dimana beliau saat bulan puasa. Staminanya begitu enerjik mengantarkan rihlah da’wahnya ke pelosok nusantara. Entah mungkin karena bentakan beliaulah saya mulai hadir dalam noktah kecil gerakan dakwah. Kalau tidak, mungkin trieha sudah ikonik dengan musik-musik metal, atau penyiar radio rock yang dulu pernah diimpikannya.
Sejarah lalu menyempatkan saya berkenalan dengan seorang guru. Pak Kamal atau lengkapnya Prof. Drs. Kamal Mukhtar biasa kami memanggilnya. Dalam perjalanan semobil saya menjemputnya, beliau bercerita betapa kalau sudah tua semuanya adalah ibadah. Pribadinya yang jujur, santun dan sederhana membuat wajar kalau Azyumardi Azra dan Tarmizi Taher menuakannya dan menganggap beliau seperti bapak kandungnya. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika kami memohon beliau mengisi kajian pagi beliau berpesan tak usahlah dijemput. “Jalan kaki lebih sehat untuk seusia saya..”
Kesederhanaan pula yang saya puji dalam diri Prof. Husain Haikal. Saya kira guyon beliau menjanjikan bertemu di Gedung Pascasarjana UNY pukul 06.00 WIB, pagi itu benar saya datangi tak selang lama beliau tiba dengan motor pitungnya. Beliau langsung menyalami saya, “Saya harus menjadi teladan buat mahasiswa saya…..” Setiap kali saya sowan ke rumahnya. Suaranya masih terus meledak-ledak, tentang keprihatinannya pada dunia pendidikan kita. Kami bercakap begitu santainya, tidak seperti beberapa dosen yang sok jaga wibawa.
Tentu masih banyak pula cerita, tetapi saya cuma ingin mengajak mencerna betapa kemuliaan itu hadir menyenyawa pada sikapnya, bukan sekedar hartanya, orasinya atau tulisannya. Siapa yang pernah bertamu ke rumah Pak Adaby Darban atau Prof. Achmad Mursyidi pasti bisa merasa betapa aura ketawadhuan tergurat begitu indahnya. Mereka, kalau boleh meminjam ungkapan dalam buku yang dulu saya beli, bukan cerita fiktif dari dongeng manapun. Mereka memang sungguh ada, bahkan tak jauh dari Anda!