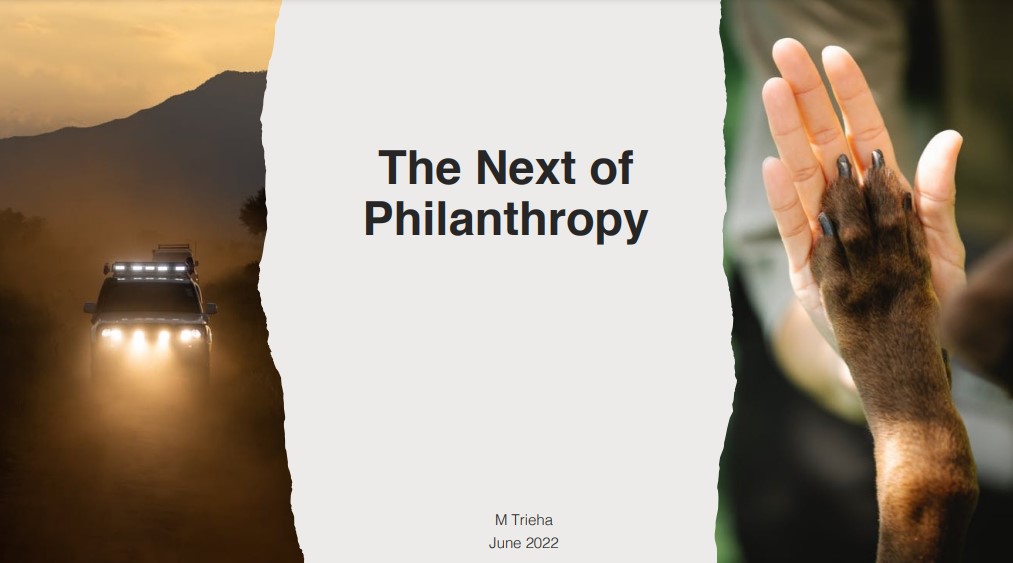Suatu pagi saat saya di Jeddah usai menjalankan ibadah umroh, kami sholat shubuh di satu masjid kecil sebelah penginapan. Usai mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Shubuh, salah satu di antara rombongan kami asal Indonesia pun berdiri dan mengumandangkan iqomat. Saya yakin maksudnya baik apalagi sudah tidak terlihat yang sholat sunnah. Tapi apa yang terjadi? Dalam bahasa Arab, yang iqomah tadi ditegur oleh seorang Arab yang menjadi petugas di sana. Ternyata untuk iqomah tidak boleh dikumandangkan oleh sembarang waktu dan sembarang orang.
Ada semacam ketentuan waktu iqomah baru bisa dilakukan sekitar 15-20 menit setelah azan, mungkin supaya jamaah yang tempat tinggalnya agak jauh bisa tetap berjamaah sejak rakaat pertama bahkan bisa juga mengerjakan sholat sunnah yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya kadang heran dengan yang biasa azan di masjid sebelah perumahan saya, dianya azan shubuh habis itu baca puji-pujian. Bukan puji-pujiannya sih yang masalah, tapi habis melantunkan senandung doa tersebut tak terlalu lama langsung iqomah. Mungkin interval azan ke iqomah cuma 5 menit. Berarti kan muadzin ini tidak sholat sunnah?
Di Saudi (dan mungkin juga di beberapa negara lain) yang menyuruh iqomah adalah imam, beda di kita, kalau di Indonesia setidaknya di tempat saya, yang iqomah ya siapa saja, lalu imam baru maju ke tempatnya. Ini masih mending imamnya ada, kalau pas lagi perjalanan, biasanya pada dorong-dorongan karena enggan menjadi imam, nasibnya yang badannya kecil jadi korban, akhirnya jadilah ia imam. Kalau dengan yang tidak kenal, biasanya saling lihat-melihat umur, atau panjang jenggot, biasanya yang lebih tua atau jenggotnya lebih lebat, didaulatlah menjadi imam.
Insiden salah paham saat sholat juga terjadi lagi di Saudi saat itu. Kita di Indonesia merasa biasa saja kalau datang ke masjid, sholat jamaah pertama sudah hampir selesai, rombongan yang baru datang pun lalu menyusun barisan dan mengangkat imam. Salahnya, saat itu jamaah kedua ini mendirikan sholat saat jamaah pertama masih belum menutup dengan salam. Usai sholat, seorang jamaah menegur sang imam, kali ini dengan bahasa Inggris, bahwa hal itu salah. Ketentuan ini menurutnya tidak hanya berlaku di masjid kecil di daerah tersebut namun juga berlaku di Masjidil Haram dan dimanapun juga.
Saya juga baru tahu ternyata ada pendapat, jika di sebuah masjid ada imam rawatib-nya atau imam yang diangkat tetap oleh negara atau dewan masjid tersebut, tidak boleh ada sholat jamaah kedua. Artinya kalau yang terlambat, dilarang atau sebagian lagi berpendapat makruh untuk membuat jamaah kedua. Setidaknya ini pendapat Imam Syafii. Pernyataan seorang mujtahid seperti ini tentu memiliki sumber rujukan. Diantaranyalah pernyataan Al Hasan Al Bashri yang mengatakan,“Para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, jika masuk masjid dan mendapatkan imam telah shalat, maka mereka shalat sendiri-sendiri.”
Mereka berdalil dengan hadits Abu Bakroh Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi: “Sesungguhnya Rasulullah datang dari pinggiran Madinah ingin menunaikan shalat. Lalu mendapati orang-orang telah selesai shalat berjama’ah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan mengumpulkan keluarganya dan mengimami mereka shalat.”
Hadits ini menunjukkan, tidak bolehnya jama’ah kedua. Karena seandainya diperbolehkan, tentu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak meninggalkan keutamaan masjid Nabawi. Ibnu ‘Abidin menyatakan dalam Hasyiyah Radul Mukhtar (1/553), “Seandainya diperbolehkan jama’ah kedua, tentu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memilih shalat di rumah dari berjama’ah kedua di masjid.”
Demikian juga atsar sahabat Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan Imam Abdirrazaq Ash Shon’ani dari Ma’mar dari Hammad bin Ibrahim, bahwa Al Qamah dan Al Aswad berangkat bersama Ibnu Mas’ud ke masjid. Lalu orang-orang menyongsong mereka dalam keadaan telah shalat. Lalu Ibnu Mas’ud pulang bersama keduanya ke rumah. Salah seorang mereka lalu berdiri di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Ibnu Mas’ud mengimami mereka shalat.
Seandainya jama’ah kedua diperbolehkan, tentulah Ibnu Mas’ud tidak berjama’ah di rumah. Apalagi berjama’ah di masjid jelas lebih utama. Demikian juga sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lainnya, tidaklah shalat sendiri-sendiri, padahal mampu untuk melakukan jama’ah.
Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat Sahnun dari Ibnul Qasim dari Malik dari Abdurrahman Al Mujabbar. Beliau berkata,“Aku masuk bersama Salim bin Abdillah pada satu masjid jami’ dalam keadaan orang-orang telah selesai shalat. Lalu mereka berkata,’Mengapa tidak shalat berjama’ah?’ Salim bin Abdillah bin Umar menjawab,’Tidak boleh shalat berjama’ah dalam satu shalat pada satu masjid dua kali.” Pernyataan Imam Salim bin Abdillah bin Umar ini menunjukkan tidak dibolehkannya berjama’ah lebih dari satu pada satu masjid. Hal ini juga disepakati oleh sejumlah tabi’in, diantaranya Ibnu Syihab, Rabi’ah dan Yahya bin Sa’id. (sumber : almanhaj.or.id).
Diantara hikmah aturan tersebut adalah, dengan adanya imam tetap, jamaah bisa ditegakkan lebih teratur dan tepat waktu. Ketidakbolehan menegakkan sholat kedua juga mendorong masyarakat untuk bergegas sesegera mungkin menuju masjid usai azan dikumandangkan. Tentu harus dibuat sistemnya terlebih dahulu, misal : berapa standar waktu azan ke iqomah, berapa luasan masjid untuk bisa menampung seluruh jamaah dalam satu daerah, fasilitas wudhu dan MCK (supaya kalaulah mengantri tidak terlalu lama), pengeras suara menjangkau wilayah dengan jelas, dan sebagainya. Jika itu semua belum terpenuhi tentu kurang bijak jika ketentuan larangan jamaah kedua diberlakukan. Meskipun asal menyerah dengan keadaan juga tidak dianjurkan.
Ketentuan di atas tidak berlaku bagi masjid yang tidak memiliki imam tetap, seperti masjid atau musholla tempat lalu lalang orang seperti di SPBU, pasar, pusat belanja, dan sejenisnya. Pertanyaannya mengapa di masjid residensial, alias di perumahan, tidak banyak yang memiliki imam tetap? Ini penting untuk kita wacanakan dan tuntaskan. Masih berkembang di kita, mengangkat imam tetap itu tidak urgen, membiayai hidup seorang imam dan petugas masjid tidaklah seprimer iuran sampah dan keamanan komplek perumahan. Termasuk juga ada persepsi miring bahwa yang menjadi petugas di masjid adalah orang-orang yang kebetulan tak punya pekerjaan, kata lain dari dhuafa yang harus disantuni. Kesan ini bukan basa-basi, karena saya dulu saat mahasiswa juga pernah tinggal di sebuah asrama masjid dan rasanya persepsi ini masih berkembang saat ini.
Semoga tulisan ini sedikit menggelitik untuk melihat kembali sholat kita, kualitas dan kuantitasnya, juga masjid kita, pengelolaannya dan pemakmurannya.